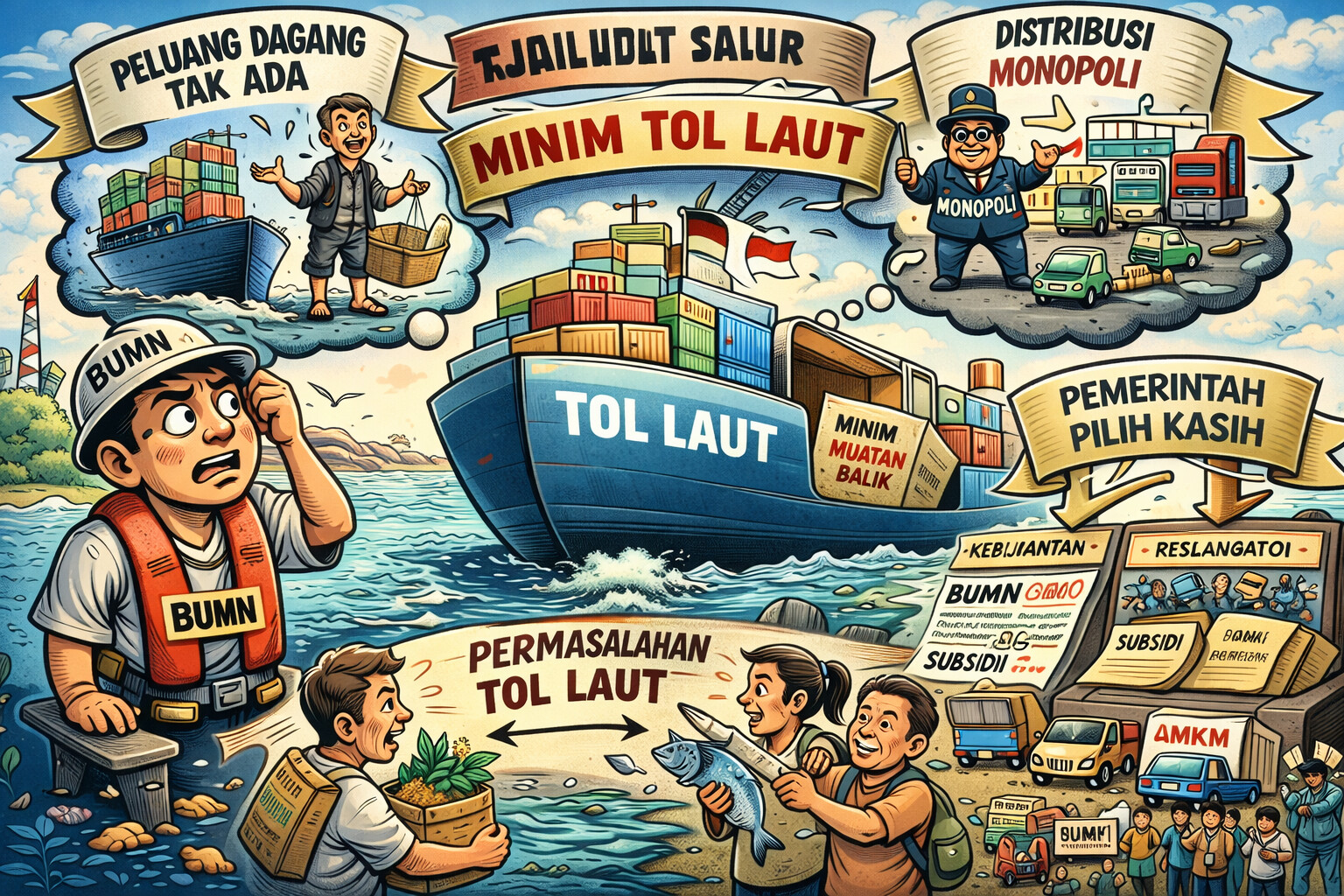Catatan Redaksi

Hampir genap sebulan, dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh seseorang telah mengguncang negeri kita tercinta. Pro dan kontra pun berkecamuk di setiap ranah-ranah publik dan jagat media sosial, hingga meningkatkan eskalasi konflik di antara masing-masing pihak (pro dan kontra). Pihak yang pro di sini melihat pernyataan seseorang tersebut wajib diproses hukum karena telah menyakiti umat muslim baik di Indonesia maupun di seluruh dunia. Sementara pihak yang kontra menyebut yang bersangkutan tidak bersalah.
Berbagai dimensi pun diutarakan oleh-oleh masing kubu hingga puncaknya pada Jumat 4 November 2016 silam, Aksi Bela Islam II berakhir pada kericuhan. Setiap pihak pun saling menuding satu sama lain. Sementara Presiden Joko Widodo yang tak hadir di Istana Merdeka saat itu sudah mengingatkan agar persatuan dan perdamaian di NKRI tetap dijaga. Beruntungnya pesan itu tersampaikan dengan baik oleh para aparat TNI dan Polri yang berjaga dan para pengunjuk rasa.
Kendati menjelang malam hari terdapat kericuhan, seluruh pihak sudah menyadari bahwa fenomena itu disebabkan oleh ulah para provokator. Dan bukan pada tulisan ini pula tempat memvonis dan menuduh siapa provokatornya.
Ya, provokator ibarat duri dalam daging yang meruntuhkan persatuan dan kesatuan serta perdamaian. Dengan kata lain, provokator telah memecah belah bangsa yang bersatu dan membuat kegaduhan di mana masing-masing pihak terus bertikai. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pro·vo·ka·tor (n) ialah orang yang melakukan provokasi: perang terselubung itu melibatkan dinas rahasia, — teroris, dan pembunuh. Singkatnya orang yang merusak perdamaian.
Adanya provokator tersebut, menyebabkan persatuan Indonesia terhitung dari tahun 1998 berada di ujung tanduk. Meskipun, Alhamdulillah, upaya provokator itu untuk memecah belah bangsa Indonesia boleh dibilang belum berhasil hingga saat ini. Namun, perpecahan tetap menjadi ancaman serius bagi bangsa yang baru memperingati milad-nya ke-88 (28 Oktober 2016) ini.
Filosofi Laut
Pulau-pulau yang dipisahkan oleh lautan sudah sekian lama memiliki pola hubungan satu sama lain dalam bentuk perdagangan hingga pernikahan. Sehingga fungsi laut bagi bangsa Indonesia bukan lah sebagai pemisah melainkan pemersatu. Hal tersebut sudah ditegaskan oleh Ir Djuanda Kertawidjaja dalam deklarasi sakralnya pada 13 Desember 1957 yang memperkuat makna Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 dan Proklamasi 17 Agustus 1945.
Secara fisiknya, laut yang merupakan daerah rendah dan panas, memiliki fungsi untuk mendamaikan jiwa-jiwa yang terbakar amarah. Laut merupakan muara terakhir dari setiap aliran air di daratan yang tetap memancarkan rasa asin sebagai simbol dari penawar dan penetral.
Dalam filosofi Jawa tentang laut dijelaskan dalam konsep kepemimpinan Hasta Brata (Delapan karakter Pemimpin). Sifat laut (samudro) menjadi salah satu karakter yang wajib dimiliki oleh seorang pemimpin. Yakni bersifat luas dan lapang sebagai simbol dari kelapangan dada dan keluasan hati, serta ilmu pengetahuan.
Dalam konteks kekinian seorang pemimpin yang menguasai sifat samudra akan mampu menerima kritikan dengan lapang dada, siap diberi saran sekalipun itu oleh bawahannya. Dia tidak akan melihat siapa yang berbicara, tetapi apa yang dibicarakan. Selain itu, dia akan menyediakan waktu dan selalu terbuka untuk menampung keluhan rakyatnya.
Di sisi lainnya, keluasan itu juga menggambarkan keluasan ilmu pengetahuan dari seorang pemimpin. Sehingga, menurut ajaran Ki Hajar Dewantara, pemimpin yang berilmu tinggi dapat menjalankan fungsinya yaitu di depan orang yang dipimpinnya (Ing ngarso sung tulodho), di tengah orang yang dipimpinnya (Ing madyo mangun karso) dan di belakang orang yang dipimpinnya (Tut wuri handayani).
Dalam konteks ini, tetaplah pemimpin sebagai manusia biasa memiliki keterbatasan sehingga diperlukan ruang musyawarah sebagai wadah untuk bertanya dan memohon masukan. Maka dari itu peranan para penasehat yang notabene orang-orang berilmu atau ulama (dalam bahasa Islam) dibutuhkan agar kebijakan pemimpin tidak salah arah dan menyimpang dari ketetapan-Nya.
Beberapa puluh tahun dari filosofi kepemimpinan yang ditelurkan oleh Ki Hajar Dewantara itu, istilah ocean leadership atau kepemimpinan yang bervisi maritim mulai diperkenalkan oleh Bung Karno pasca Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Makna dari istilah itu bukan hanya pemimpin yang hanya mengurusi laut dari seluruh dimensi saja melainkan juga menyimbolkan luasnya ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh orang dipercaya sebagai Wakil Tuhan di muka bumi.
Pancasila dan Ocean Leadership
Semua anak bangsa ini bersepakat bahwa Pancasila merupakan alat pemersatu bagi ke-bhinekaan Indonesia sehingga tersemat istilah Bhineka Tunggal Ika pada lambang Garuda Pancasila. Soal persatuan Indonesia pun juga ditegaskan dalam sila ketiganya yang menguatkan sila pertama dan kedua. Karena sesungguhnya sila-sila dalam Pancasila itu merupakan suatu hirarki dan satu kesatuan.
Sementara, sudah pasti sila ketiga akan dikuatkan oleh sila keempat yang berbunyi “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawatan perwakilan”. Makna hikmat kebijaksanaan itu ialah orang-orang yang berhikmat dan menggali ilmu pengetahuan sehingga diperoleh kebijaksanaan (Kodri, 18:2001).
Sila ini merupakan merupakan feed back dari Ketuhanan YME, sehingga bisa dimaknakan bahwa pemimpin yang berilmu ialah orang yang mengerti akan nilai-nilai ketuhanan. Selain itu, dia juga memahami perjalanan sejarah bangsanya.
Oleh karena itu filosofi laut yang melekat pada kepemimpinan bervisi maritim akan menguatkan persatuan Indonesia. Tentunya dengan visi poros maritim, seluruh rakyat Indonesia percaya bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) merupakan figur yang dapat mempersatukan bangsa Indonesia yang kini tengah terkoyak oleh suatu fenomena sosial.
Dengan kebijakannya yang adil kelak dalam menyelesaikan kasus ini, Presiden Jokowi dituntut dapat menentramkan jiwa-jiwa bangsa Indonesia yang kini mengalami goncangan (bukan sebaliknya), sekaligus ujian untuk mewujudkan poros maritim dunia. Terus ajaklah rakyat ini untuk tidak memunggungi laut. ‘Mari ramai-ramai pergi ke laut’, begitulah ending dari lagu ‘Nenek Moyangku seorang Pelaut’.
Di laut, manusia akan belajar soal keluasan hati dan makin mengenal Sang Penciptanya. Sehingga manusia-manusia yang terus menggali ilmu akan memiliki sikap rendah diri (tawadhu), bukan sebaliknya menjadi pribadi-pribadi yang angkuh.
Jika demikian, jangan salahkan jika laut dapat menimbulkan tsunami karena pemimpinnya sudah tidak lagi menjaga keseimbangan alam!